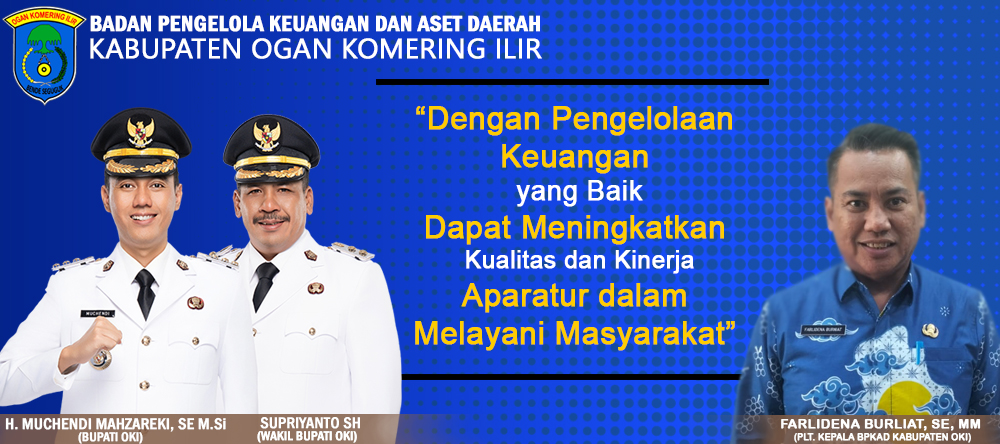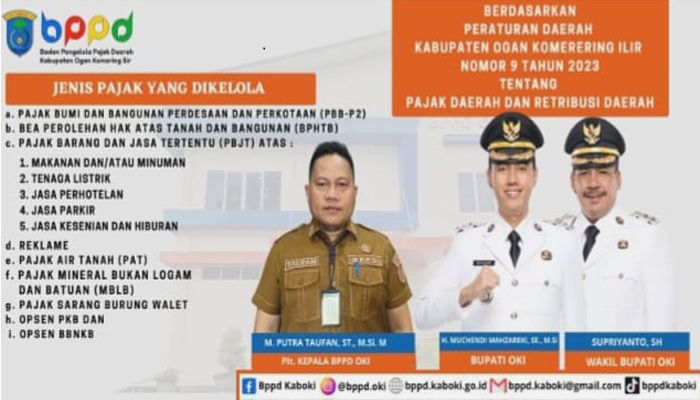Di tengah gemuruh layar lebar dan lampu-lampu gala festival, ada gerakan lain yang tumbuh tenang dari tepian: Komunitas Cinta Film Indonesia (KCFI). Bukan klub kritik elit, melainkan jaringan akar rumput yang membidik satu tujuan sederhana namun radikal—mendemokratisasi akses terhadap film.
Di bawah kepemimpinan Budi Sumarno, KCFI menempuh perjalanan dari ruang-ruang diskusi di Jakarta menuju pojok-pojok kota dan desa, merintis workshop, nobar, kompetisi kreatif, hingga produksi film yang bersandar pada sejarah lokal. Gerakan ini menjanjikan: film bukan sekadar industri, tetapi ruang publik yang mesti dimiliki oleh masyarakat sendiri.
Asal-Usul dan Gagasan Founding
Tanggal 29 Maret 2016 tercatat sebagai titik lahir KCFI. Di balik tanggal formal itu ada keresahan yang lebih tua: industri perfilman Indonesia yang semakin tersentralisasi di ibukota.
Di tengah situasi itu, nama Budi Sumarno muncul sebagai penggerak—seorang kurator, produser, dan pendidik yang sejak lama menaruh perhatian pada ruang-ruang kreatif nonkomersial.

Budi bersama dua tokoh lain—Adisurya Abdy dan Bernhard Uluan Sirait—menginisiasi sebuah komunitas yang bukan hanya menggelar pemutaran, tetapi juga menanam keterampilan teknis, membangun jaringan, dan menyuarakan inklusi.
Gagasan KCFI sederhana: bila industri terlalu elit, komunitas harus menjadi medium alternatif. Dari kelompok peminat, komunitas dapat mengembang menjadi wahana produksi, pendidikan, dan dokumentasi budaya.
Semangat ini mendorong KCFI menjadi lebih dari sekadar klub nonton; mereka menginginkan film sebagai alat pendidikan publik, pengingat sejarah, dan sarana pemberdayaan sosial.
Visi, Misi, dan Praktik Inklusi
Visi KCFI terangkai dari dua kata yang tampak mudah: inklusif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, inklusi KCFI berwujud dalam upaya membuka akses bagi beragam kelompok—pelajar, pekerja nonformal, pembuat film amatir, hingga penyandang disabilitas.
Kegiatan yang rutin diselenggarakan meliputi short course teknis (kamera, editing), lokakarya penulisan naskah, kompetisi video kreatif untuk siswa, serta pemutaran terbuka yang diikuti diskusi publik.
Penting dicatat, inklusi bukan hanya retorika. Ada bukti aktivitas di lapangan: program pelatihan bagi penyandang disabilitas, kompetisi video di Bali untuk kalangan sekolah, serta kolaborasi dengan komunitas lokal untuk penggalian materi sejarah.
KCFI menempatkan proses edukasi sebagai prasyarat agar komunitas lokal mampu memproduksi karya sendiri—sebuah strategi untuk mempertahankan kesinambungan gerakan.
Menjadi Jaringan: Ekspansi ke Daerah
Jejak KCFI mulai terlihat di berbagai wilayah: Bali, Semarang, Sumatera Selatan, dan kota-kota lain.
Namun perlu hati-hati membaca sebaran itu. KCFI bukanlah organisasi yang langsung membuka cabang administratif di setiap kabupaten; penyebarannya sering berupa perintisan komunitas setempat yang menamakan diri bagian dari jejaring KCFI.

Di Bali, misalnya, KCFI aktif menggelar kompetisi untuk siswa; di Semarang, mereka menjadi fasilitator nobar dan diskusi.
Di kota dan daerah lainnya, sebagaimana disebutkan Ketua Umum Budi Sumarno, KCFI juga sudah terbentuk di Lumajang, Bandung, Majalengka, Surabaya, Indramayu, Bogor, Banten, Bekasi dan Palu.
Di Sumatera Selatan, pada Sabtu 29 November 2025 organisasi ini melantik pengurus wilayah yang menegaskan ambisi memproduksi film sejarah lokal—sebuah loncatan dari sekadar apresiasi ke produksi.
Pengalaman ini memperlihatkan dua dinamika: pertama, kekuatan jejaring yang lahir dari inisiatif lokal; kedua, keterbatasan data administratif.
Hingga kini belum ada inventaris publik yang merinci berapa kabupaten/kota yang benar-benar aktif dalam jaringan ini.
Informasi yang ada umumnya bersifat naratif: laporan kegiatan, rilis media lokal, atau profil organisasi di platform relawan. Untuk seorang peneliti, celah data ini membuka ruang riset penting: mendokumentasikan hubungan formal-informal antara pusat dan wilayah.
Aktivitas yang Nyata dan Dampaknya
Aktivitas KCFI beragam: dari edukasi teknis hingga produksi film berbasis riset sejarah.
Program kreatif di Bali menargetkan peserta sekolah; di Semarang, nobar menjadi medium politik budaya—ruang publik di mana film dipakai untuk mengangkat isu; di Sumsel, rencana memproduksi film sejarah menunjukkan ambisi jangka panjang.
KCFI juga menaruh perhatian pada representasi kelompok marjinal—misalnya upaya agar penyandang disabilitas tidak hanya jadi penonton, melainkan pembuat konten.
Dampak kegiatan ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Di tingkat lokal, pelatihan meningkatkan kemampuan teknis peserta; kompetisi menstimulasi produksi konten lokal; sementara pemutaran publik membuka diskursus budaya.

Secara kultural, gerakan seperti KCFI membantu memelihara ingatan kolektif—mengangkat kisah-kisah lokal yang seringkali luput dari arus industri komersial.
Keterbatasan dan Tantangan Organisasi
Tumbuhnya jaringan komunitas tidak lepas dari tantangan. Pertama, masalah pendanaan. Program-program komunitas seringkali bergantung pada sumber daya lokal, sponsor sempit, atau kegiatan berbiaya kecil.
Kedua, struktur organisasi yang longgar membuat penetapan standar kualitas produksi dan manajemen wilayah menjadi sulit.
Ketiga, kurangnya data terpusat menimbulkan masalah akuntabilitas: bagaimana memastikan kegiatan wilayah berkelanjutan dan tidak terputus ketika inisiator lokal pindah atau kehilangan sumber daya?
Lebih jauh, ada juga pertanyaan tentang legitimasi—antara komunitas yang bergerak secara mandiri dan klaim sebagai bagian jejaring nasional.
Ketika media menulis “KCFI hadir di X daerah”, seringkali itu berarti ada aktivitas bernama KCFI, bukan cabang formal dengan AD/ART dan struktur keanggotaan yang terdaftar.
Peluang Penelitian & Rekomendasi
Untuk sejarawan budaya dan peneliti kebijakan seni, KCFI menawarkan studi kasus menarik: bagaimana inisiatif lokal mengisi kekosongan representasi budaya dalam ekosistem media.
Beberapa rekomendasi penelitian: mendata jaringan KCFI secara sistematis; memetakan dampak program edukasi terhadap karir kreatif peserta; meneliti model pendanaan yang paling berkelanjutan untuk komunitas film; dan mengkaji representasi isu-isu lokal yang dibawa ke layar oleh komunitas ini.
Dari sisi praktis, KCFI dapat memperkuat keberlanjutan dengan mengembangkan modul pelatihan standar, membangun database cabang/aktivitas, serta menjajaki kemitraan jangka panjang dengan institusi pendidikan dan badan kebudayaan.
Film sebagai Ruang Kolektif
KCFI berdiri pada titik temu antara cinta dan ketidakpuasan: cinta pada film, dan ketidakpuasan pada sistem yang eksklusif. Dalam beberapa tahun, gerakan ini berhasil membuka ruang bagi banyak pihak untuk belajar, bertemu, dan berkarya.
Namun perjalanan ke depan menuntut struktur yang lebih rapi, sumber daya yang stabil, dan dokumentasi yang kuat agar keberadaan komunitas ini tidak hanya menjadi cerita hangat di headline, melainkan warisan institusional bagi perfilman Indonesia.
Jika industri film nasional ingin benar-benar inklusif, tanggung jawabnya tak lagi hanya pada rumah produksi besar atau festival internasional.
Ia ada pada ruang-ruang kecil di mana orang belajar menyalakan kamera pertama kali, di mana cerita lokal difilmkan untuk pertama kali. KCFI memilih mengambil tugas itu—dengan segala keterbatasan dan keberaniannya.**