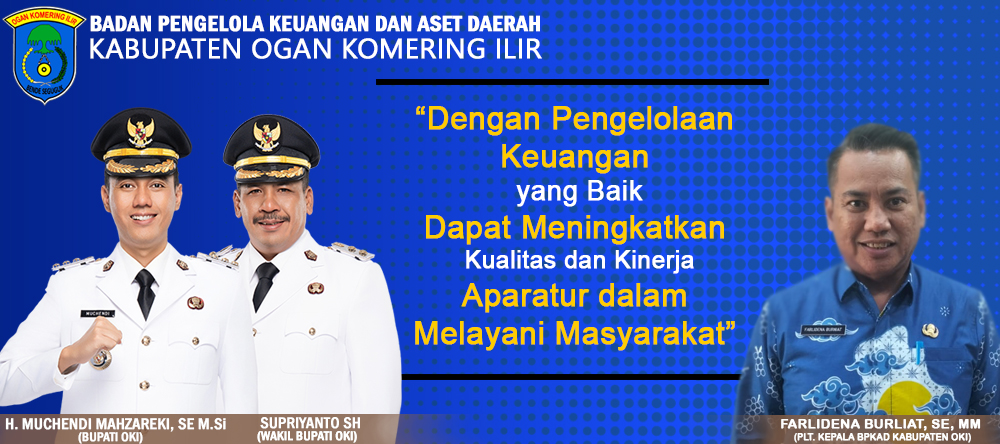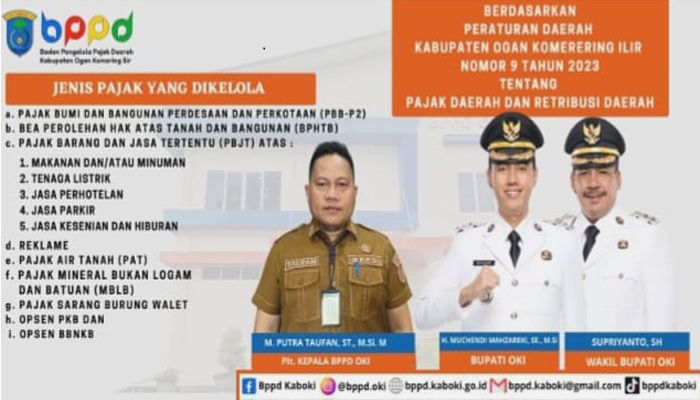Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kitab puisi Kekibang karya Yudistio Ismanto, mari kita buka dulu lembaran sejarah sastra Indonesia. Bukan sebagai nostalgia, tapi sebagai pijakan. Karena puisi, cerpen, novel, drama—semuanya lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari rahim zaman, dari keresahan sosial, dari denting politik, dari desir budaya yang terus berganti.
Ada yang menyebut, perjalanan sastra Indonesia bisa dibagi jadi beberapa angkatan. Balai Pustaka (1917), tempat sastra kita masih malu-malu menyapa pembacanya. Lalu datang Pujangga Baru (1933) yang lebih percaya diri, menawarkan semangat kebangsaan dan pembaruan bahasa. Kemudian meledaklah Angkatan ’45, generasi pemberontak yang tidak hanya melawan penjajah, tapi juga menolak tatanan lama. Di sana berdiri nama-nama seperti Chairil Anwar, Rendra, Ajip Rosidi, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, A.A. Navis.
Lalu datang Angkatan ’66, para penolak penyelewengan. Tapi kemudian di era ’80-an, suara kritik itu meredup. Bukan padam, tapi diseret masuk ke ruang bawah tanah. Orde Baru bukan sekadar pemerintahan, tapi semacam “penguasa cuaca”—yang bisa menentukan kapan boleh turun hujan puisi, dan kapan harus kering kerontang oleh nyanyian hiburan.
Kemudian tiba era Reformasi. Angin mulai berubah arah. Sutardji Calzoum Bachri, Ahmadun Yosi Herfanda, Acep Zamzam Noer muncul menyodorkan puisi dengan napas sosial-politik yang lebih terbuka. Perubahan kepemimpinan dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, hingga Megawati, semua itu ikut memengaruhi warna tinta yang mengalir dari pena para penyair.
Masuk ke era 2000-an, muncul generasi baru. Korrie Layun Rampan menyebutnya sebagai Angkatan 2000. Di sini bertebaran nama-nama lama dan baru. Ada Afrizal Malna, Seno Gumira Ajidarma, Ayu Utami, Dorothea Rosa Herliany. Tapi menariknya, nama-nama seperti Habiburrahman El Shirazy dan Andrea Hirata tidak masuk. Entah karena pilihan, entah karena “hoki” dianggap tak cukup puitik di mata kritikus sastra.
Sastra Daerah: Di Antara Kenangan dan Kenyataan
Ngomong-ngomong soal sastra daerah, kita sering terpeleset pada definisi. Banyak yang mengira, asal ceritanya soal daerah, maka otomatis itu sastra daerah. Padahal, seperti dikatakan A. Rapani Igama, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, ya itu tetap sastra nasional. “Sastra daerah itu ya ditulis dalam bahasa daerah,” ujarnya. Tegas dan jujur.
Erwan Surya Negara, budayawan Sumsel, pernah gusar. Kenapa kita kalah dari Jawa atau Sunda, yang dengan bangga menulis dalam bahasa sendiri? Kenapa kita minder menulis dalam dialek kampung halaman kita sendiri? Harusnya kita bangga. Kita punya banyak cerita, banyak kosakata, banyak hikmah dari tanah kelahiran kita yang belum banyak disentuh pena.
Dari Empat Lawang, muncullah sosok yang dijuluki Penyair Gunung, Syamsu Indra Usman. Dari Ulu Musi, beliau menulis dalam bahasa ibu: Kampuh Keluang, Behuk Atus, dan lainnya. Di Palembang, ada Iqbal J. Permana dengan Seluang Poetica, yang bahkan sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia. Di Lahat, ada Yudistio Ismanto dan Jajang R. Kawentar yang mulai menapaki jalan sunyi ini. Sunyi, tapi bermakna.
Sastra: Jalan Sunyi yang Tak Selalu Mengenyangkan
Percaya atau tidak, sastra daerah adalah ibu kandung sastra nasional. Ia hidup dari cerita lisan, dongeng pengantar tidur, mitos dan legenda: Si Pahit Lidah, Putri Pinang Masak, Dayang Rindu, Bujang Jelihim, Batu Betangkup. Semua itu adalah akar yang menopang pohon besar sastra Indonesia hari ini.
Tapi jalan ini bukan jalan aspal. Banyak bebatuan tajam, banyak semak berduri. Menjadi sastrawan daerah seringkali berarti “memunggungi dapur” dan melupakan impian kaya dari buku. Cetak buku pakai dana sendiri, dijual sendiri, dibaca sendiri, direview sendiri.
Kalau beruntung, ada pengadaan buku dari dinas. Kalau tidak, ya anggap saja latihan ikhlas. Tapi kalau pun Tuhan suatu saat berkehendak memberi kekayaan lewat jalan sastra, ya jangan menolak. Kepantasan itu bisa datang kapan saja—asal kita masih menulis dan menulis dan menulis.
Dan inilah makna sejati dari menjadi penyair: bukan untuk ketenaran, bukan untuk uang, tapi untuk menyampaikan kebenaran, nilai, dan kejujuran dalam bahasa yang indah. Kepuasan terbesar seorang penyair adalah ketika puisinya dibaca, direnungkan, dan mungkin diam-diam mengubah seseorang.
Kekibang: Orang-orangan di Sawah Kehidupan
Nah, mari kita kembali ke Kekibang. Judul yang sederhana tapi tajam. Kekibang itu… orang-orangan sawah. Sosok yang berdiri, tapi kosong. Tegak, tapi diam. Ada, tapi bukan siapa-siapa. Kadang diabaikan, kadang ditakuti. Simbol dari banyak hal—terutama dalam dunia sosial politik kita hari ini.
Saya tidak tahu apakah Yudistio bermaksud demikian, tapi saya merasa Kekibang bukan sekadar simbol estetika. Ia adalah refleksi dari manusia modern yang makin hari makin kehilangan jiwanya. Manusia yang rela menjadi alat. Yang hidup sekadar mengais nasi di sawah-sawah struktur negara dan keluarga.
Dan jika Kekibang itu adalah representasi kita hari ini—yang pura-pura kuat tapi rapuh di dalam, yang berdiri karena disuruh, yang diam karena takut—maka puisi-puisi Yudistio adalah tamparan yang elegan. Tamparan yang disampaikan dengan lembut, dalam bait-bait yang penuh permenungan.
Akhir Kata: Jangan Malu Menjadi Gunung yang Pelan Menaik
Menjadi sastrawan daerah, seperti Yudistio, Syamsu Indra (skrg almarhum), atau Iqbal, bukan perkara gaya. Ini perkara pilihan hidup. Pilihan untuk tetap menjadi suara di tengah sunyi. Pilihan untuk tetap menjadi pohon di tengah ladang beton. Pilihan untuk tetap percaya bahwa kata-kata bisa mengubah dunia, meski dimulai dari kampung sendiri.
Kalau mau sawah berubah, jangan cuma tunggu hujan dari langit. Mulailah dari menanam benih, dari menggali tanah. Jangan berharap batu di gunung runtuh sendiri, kalau kita tak pernah naik ke atas dan mendorongnya pelan-pelan.
Dan di titik itulah kita tahu: Kekibang bukan hanya buku. Ia adalah cermin. Ia adalah doa yang diam. Ia adalah suara sunyi dari ujung desa—yang seharusnya kita dengarkan lebih dalam.
*) Diolah dari dari Makalah yang pernah disampaikan pada diskusi Sastra 18 Oktober 2012 di Kabupaten Lahat | Editor : Warman P